‘Dokter bilang saya kena kanker mulut, saya langsung takut’ – Tradisi mengunyah pinang di Papua, dilema antara budaya dan risiko kesehatan

Sumber gambar, Muhammad Ikbal Asra
Tradisi mengunyah pinang yang dicampur dengan kapur dan buah sirih telah mendarah daging dalam hidup warga Papua dan kerap digunakan dalam berbagai ritual adat. Namun, di balik nilai budayanya, mengunyah pinang berisiko menimbulkan masalah kesehatan serius, seperti kanker mulut.
Tradisi mengunyah pinang yang dicampur dengan berbagai bahan lain sebagai “ramuannya”—seperti sirih, kapur gambir dan tembakau—telah berlangsung selama berabad-abad di Asia Tenggara. Di Indonesia, tradisi ini berkembang di Sumatra, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga Papua.
Di Papua, kebiasaan “makan pinang” telah berlangsung secara turun temurun dan dilakukan oleh semua kalangan usia, bahkan di tempat umum, berbeda dengan daerah lain yang umumnya hanya oleh orang tua di pedesaan.
Cara mengunyah pinang di Papua juga berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Jika di Jawa tradisi ini dilakukan tanpa pinang dan menggunakan kapur mentah, kebiasaan ini dilakukan dengan menggunakan pinang matang dan kapur kering di Papua.
Pada 2003, Badan Internasional untuk Penelitian Kanker (IARC)—sebuah badan ilmiah di bawah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)—menyimpulkan bahwa kebiasaan mengunyah sirih dapat menyebabkan kanker mulut, kanker tenggorokan bagian atas (faring), dan kanker kerongkongan.
Akhir dari Paling banyak dibaca
Buah pinang yang menjadi bahan utama dalam tradisi ini dikategorikan sebagai zat karsinogenik yang berbahaya meskipun dikonsumsi tanpa tembakau.

Sumber gambar, Muhammad Ikbal Asra
Kanker mulut menempati posisi kedua jenis kanker yang banyak terjadi di Papua setelah kanker payudara, menurut data Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura. Jumlah ini mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun.
Kendati memiliki risiko kesehatan yang serius, banyak warga Papua—terutama kaum perempuan—tetap melestarikan kebiasaan mengunyah pinang ini, menganggapnya sebagai bagian tak terpisahkan dari budaya dan “identitas” mereka.
Lantas, bagaimana perempuan dan generasi muda Papua, yang terjebak dalam dilema antara nilai budaya dan ancaman kesehatan, memaknai tradisi mengunyah pinang?
‘Dokter bilang saya kena kanker mulut, saya langsung takut’
Welmince Florida Lomo, telah mengunyah pinang sejak kecil—seperti warga Papua pada umumnya.
Perempuan berusia 45 tahun tersebut mengaku telah melakukan kebiasaan ini sejak berusia tujuh tahun.
“Waktu itu, semua orang makan pinang dari orang tua sampai anak-anak. Sudah terbiasa,” ujar Welmince kepada wartawan Muhammad Ikbal Asra yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.
Di Papua, buah pinang dan bahan pelengkapnya mudah ditemukan di pinggir jalan. Satu paket berisi 10 buah pinang, kapur, dan buah sirih dijual seharga Rp10.000.
Sejak itu, kebiasaan makan pinang menjadi bagian hidup sehari-hari perempuan yang tinggal di Skouw Sae, Jayapura ini. Namun pada 2015, semuanya berubah.

Sumber gambar, Muhammad Ikbal Asra
Setelah bertahun-tahun mengunyah pinang yang dicampur sirih dan kapur, ia mulai merasakan luka di bagian dalam mulutnya.
“Luka itu tidak sembuh. Malah tambah besar, tambah sakit,” kenangnya.
Luka tersebut terus bertahan selama lima tahun. Welmince tak langsung memeriksakan diri ke dokter karena menganggapnya hal yang wajar.
Kala luka itu semakin membesar, dia merasa kesulitan berbicara dan makan. Welmince pun memeriksakan diri ke puskesmas yang kemudian merujuknya ke RSUD Jayapura.
Oleh dokter yang memeriksanya, dia diagnosis menderita kanker mulut.
“Waktu dokter bilang saya kena kanker mulut, saya langsung takut,” ujarnya.
“Di kampung, sudah lima orang meninggal karena kanker. Saya pikir, saya akan jadi yang keenam.”
Welmince kemudian menjalani dua kali operasi yang dilanjutkan dengan kemoterapi selama tiga bulan. Ia menyebut prosesnya berat, tetapi akhirnya ia dinyatakan sembuh.
“Puji Tuhan, saya kuat. Habis kemo, saya sehat kembali,” katanya.
Welmince adalah salah satu pasien kemoterapi yang ditangani dokter Jan Frits Siauta, Kepala Unit Kemoterapi RSUD Jayapura.
Dokter Jan menjelaskan bahwa kandungan karsinogen dalam kapur dan sifat anestesi lokal pada pinang dapat menyebabkan infeksi berulang di area mulut, yang berpotensi berkembang menjadi kanker.
Sementara kapur yang digunakan dalam campuran pinang, kata dokter Jan, bersifat panas dan dapat menyebabkan luka atau erosi di jaringan mulut.

Sumber gambar, Muhammad Ikbal Asra
Luka yang terjadi berulang kali inilah yang bisa memicu mutasi sel, salah satu teori awal terbentuknya kanker.
“Buah Pinang memiliki efek seperti anestesi lokal, sementara kapur bersifat korosif,” ujar Jan ketika ditemui di kantornya.
“Ketika mulut terluka secara terus-menerus, risiko infeksi kronis meningkat, dan di situ lah potensi mutasi sel muncul. Inilah yang menjadi pintu masuk kanker,” ungkapnya.
RSUD Jayapura mencatat bahwa kanker mulut adalah kasus terbanyak kedua setelah kanker payudara di wilayah Papua. Ini berbeda dengan daerah lain di Indonesia yang didominasi kanker serviks.
“Jumlah kasus kanker mulut justru terus meningkat dari tahun ke tahun,” cetusnya.
Pada 2023 silam, tercatat ada 22 kasus kanker mulut—yang dikaitkan dengan kebiasaan mengunyah pinang—yang ditangani RSUD Papua.
Jumlah ini mengalami peningkatan pada 2024, menjadi 27 kasus. Adapun dalam lima bulan pertama 2025 telah tercatat 29 kasus kanker mulut.
Salah satu penyebab kenaikan kasus kanker mulut, kata dokter Jan, adalah akses informasi dan transportasi lebih baik, sehingga pasien dari pelosok yang sebelumnya tidak terdata, kini mulai terdeteksi.
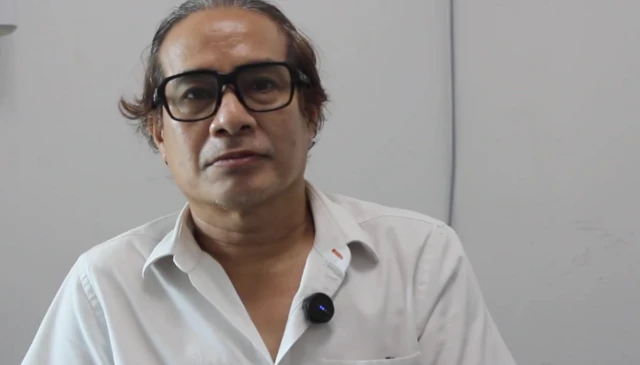
Sumber gambar, Muhammad Ikbal Asra
Berbeda dengan kebiasaan merokok—yang juga memiliki risiko menyebabkan kanker—yang didominasi laki-laki, mengunyah pinang lazim dilakukan pria dan perempuan di Papua.
“Di sini, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mengunyah pinang. Jadi, angka kasusnya juga tidak jauh berbeda,” jelas dr. Jan.
Akan tetapi, sebagian besar pasien datang dalam kondisi stadium lanjut, yang membuat penanganan menjadi sangat sulit.
“Hampir 100 persen pasien kanker mulut tipe squamous cell carcinoma yang datang ke kami berakhir dengan kematian,” tambahnya.
‘Pinang bikin saya sehat’
Walaupun diklaim punya risiko kesehatan, sebagian warga Papua menganggap mengunyah pinang menyehatkan. Salah satunya adalah Petronela Merauje yang setia menjalani tradisi ini.
“Saya mulai makan pinang waktu umur 21 tahun, setelah saya menikah dan punya anak,” tutur perempuan berusia 44 tahun ini.
Baginya, pinang bukan hanya kebiasaan, tapi sudah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari yang memberi rasa nyaman dan percaya diri.
“Bangun pagi sikat gigi, langsung makan pinang. Malam sebelum tidur juga makan pinang dulu, baru sikat gigi lagi,” katanya.

Sumber gambar, Muhammad Ikbal Asra
Biasanya, warga Papua melakukan kebiasaan ini dengan memilih buah pinang muda yang segar, kemudian mencampurnya dengan buah sirih dan kapur.
Ketiganya lalu dikunyah bersamaan secara perlahan. Pahit dan sepat terasa kuat saat mengunyah pinang dan bahan pelengkapnya tersebut.
Efek dari mengunyah pinang, ludah dan bibir berubah menjadi berwarna merah menyala.
“Saya punya gigi dulu banyak yang sudah goyang, tapi sejak makan pinang, justru gigi jadi kuat. Saya malah kunyah pinang sama kulitnya, tapi tidak pernah patah.”
Tak hanya itu, ia merasa aroma mulutnya lebih segar sejak mengunyah pinang.
“Pinang bikin napas harum,” ujarnya.

Sumber gambar, Muhammad Ikbal Asra
Petronela menyebut ibu kandungnya sendiri sebagai bukti nyata bahwa pinang bukanlah biang keladi penyakit.
“Mama saya makan pinang sampai umur 85 tahun, sampai meninggal dia sehat-sehat saja. Tidak pernah kena kanker,” tuturnya.
Meski ia mengetahui banyak orang telah didiagnosis dengan kanker mulut dan bahkan menjalani operasi, Petronela mengaku belum melihat kaitan langsung antara pinang dan penyakit tersebut.
“Saya tidak pernah belajar soal pinang itu berbahaya. Saya rasa penyakit bisa datang dari mana saja, bukan cuma dari pinang. Bisa dari makanan lain juga,” katanya.
‘Pinang sebagai simbol identitas orang Papua’
Meski dianggap berisiko bagi kesehatan, tradisi mengunyah pinang masih mengakar kuat di tengah masyarakat asli Papua.
Antropolog Budaya dari Universitas Cenderawasih, Frederik Sokoy, bilang pinang bukan sekadar buah untuk dikunyah, tapi juga simbol komunikasi, kehormatan, bahkan identitas budaya.
“Usianya hampir setua manusia Papua sendiri,” ungkap Frederik.
Tradisi mengunyah pinang, kata Frederik, bermula di wilayah dataran rendah—tempat banyak pohon itu tumbuh subur—lalu menyebar ke wilayah-wilayah lain di Papua.
Menurutnya, pinang telah digunakan sejak zaman nenek moyang sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat.
“Buah pinang bukan hanya dikonsumsi untuk kesenangan pribadi, tapi menjadi medium dalam membangun relasi sosial dan menyampaikan maksud tertentu,” ujarnya.

Sumber gambar, Muhammad Ikbal Asra
Nilai budaya ini juga terdapat dalam tradisi mengunyah sirih pinang di Melayu, menurut Nining Wilujeng dalam penelitiannya, Sirih Pinang di Indonesia dan Taiwan yang dipublikasikan pada 2015.
Istilah “sekapur sirih” yang bermakna pembuka muncul dari kebiasaan menghadirkan sirih pinang sebagai hidangan pembuka saat menjamu tamu.
Frederik Sokoy kemudian menambahkan bahwa kebiasaan mengunyah pinang di Papua tak mengenal usia.
Anak-anak di kampung-kampung pun sejak usia dua tahun sudah diperkenalkan dengan pinang.
“Ada juga yang baru satu tahun sudah diberi [buah pinang], biasanya dikunyah dulu oleh orang tua lalu diberikan ke anak,” tambah Frederik.
Pinang dikonsumsi sebelum berangkat sekolah, saat istirahat, bahkan menjadi bagian dari aktivitas rumah tangga sehari-hari.

Sumber gambar, Muhammad Ikbal Asra
Frederik Sokoy menguraikan tiga makna budaya dalam tradisi mengunyah pinang di Papua.
Pertama, pinang memiliki fungsi sosial. Pada masa lalu, masyarakat Papua menyajikan pinang kepada tamunya sebagai bentuk penghormatan dan keakraban.
Kedua, pinang sebagai simbol perdamaian. Dalam banyak kasus, konflik antar individu bahkan antar kelompok bisa diredakan hanya dengan duduk bersama dan mengunyah pinang sebagai simbol perdamaian.
Ketiga, pinang memberikan semangat dan tenaga tambahan. Bagi masyarakat Papua yang banyak melakukan aktivitas fisik seperti mendayung, berjalan jauh, atau bekerja berat, pinang menjadi semacam stimulan alami.
“Ia bekerja hampir seperti rokok, tapi dari dalam. Bukan untuk menenangkan, tapi justru memberi semangat,” terang Frederik.

Sumber gambar, Muhammad Ikbal Asra
Pinang juga hadir dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan tradisional, pelantikan kepala suku maupun Ondofolo, hingga ritual-ritual lainnya.
“Dalam ritual adat, pinang adalah elemen yang tak bisa dipisahkan. Ia bagian dari simbol penghormatan dan identitas orang Papua,” tambahnya.
Di beberapa komunitas, kebisuan dalam pertemuan adat bisa dipecahkan hanya dengan pinang. Setelah diberikan pinang, barulah orang-orang mulai berbicara.
“Pinang menstimulasi percakapan. Ia membuka ruang dialog dan kesepahaman,” kata Frederik.
Dilema generasi muda Papua
Di sudut-sudut kota hingga pelosok kampung di Papua, anak-anak muda terlihat sibuk menggenggam plastik kresek kecil berisi pinang, sirih, dan kapur.
Di balik senyum merah pekat yang mengembang dari bibir mereka, tersimpan warisan leluhur, rasa bangga, juga bahaya yang diam-diam mengintai. Mulai dari luka di mulut hingga risiko kanker yang mematikan.
Antara cinta pada budaya dan panggilan untuk menjaga kesehatan, mereka kini berdiri di persimpangan yang sulit.
Meski risiko kanker mulut semakin nyata, bagi banyak pemuda Papua, meninggalkan pinang bukan perkara mudah.

Sumber gambar, Muhammad Ikbal Asra
Mengunyah pinang bukan sekadar kebiasaan, tapi bagian dari identitas mereka, seperti diutarakan salah satu perempuan muda Papua, Yokbeth Felle.
“Kalau disuruh gambarkan diri saya, saya akan bilang: saya ini pinang. Saya besar dengan pinang, hidup dari pinang,” tuturnya.
“Mama saya jualan pinang, dan saya sendiri makan pinang dari umur lima tahun.”
Yokbeth mengenal pinang sejak kecil, bahkan sebelum bisa mengunyah sendiri.

Sumber gambar, Muhammad Ikbal Asra
Ia bercerita tentang tradisi “bakho pinang”, kala orang tua atau nenek mengunyah pinang terlebih dahulu, lalu memberikannya ke anak kecil yang belum bisa mengunyah.
“Biasanya dari mama atau nenek. Mereka kunyah sampai merah, baru dikasih ke kita. Waktu bayi, kita sudah pegang sirih. Itu seperti perkenalan pertama,” ujar perempuan berusia 24 tahun ini.
Dalam sehari, Yokbeth bisa mengunyah pinang lebih dari 20 kali. Momen favoritnya? Saat hujan turun, atau sesaat setelah makan besar.
“Rasanya hangat, menyegarkan, dan bikin semangat. Kayak orang habis merokok dapat tenaga baru.”

Sumber gambar, Muhammad Ikbal Asra
Selain untuk dinikmati, pinang juga selalu hadir dalam setiap momen penting pesta adat hingga peringatan duka.
“Kalau ada kematian, biasanya tiga malam berturut-turut orang kumpul dan pasti ada pinang. Itu wajib. Orang selalu cari pinang,” ungkap Yokbeth.
Dia menambahkan, pinang punya fungsi sosial yang kuat. Ia menjadi alasan untuk berkumpul, berbincang, dan mempererat hubungan.
“Pinang itu simbol kebersamaan. Saat makan, kita ajak orang lain gabung. Jadi alat pemersatu.”
Namun, lebih dari sekadar budaya, bagi Yokbeth dan banyak anak muda Papua lainnya, pinang juga adalah gaya hidup.
“Di sini, makan pinang itu sudah biasa. Sudah jadi bagian dari siapa kita.”
Yokbeth tak memungkiri bahwa informasi terkait risiko kesehatan dalam kebiasaan yang telah mendarah daging dalam kehidupannya itu diam-diam punya risiko kesehatan telah lama beredar.
Namun, sama seperti warga Papua pada umumnya, Yokbeth masih meragukan kebenarannya.
“Orang tua kami dari dulu makan pinang, dan mereka baik-baik saja. Jadi saya tidak langsung percaya, tapi juga tidak menolak. Masih bingung, benar atau tidak.”
Menurut Yokbeth, akar masalahnya bukan pada buah pinang, namun pada kapur yang menjadi bahan campuran dalam tradisi “makan pinang” di Papua.

Sumber gambar, Muhammad Ikbal Asra
“Dulu kami pakai kapur danau, dari kulit kerang. Tidak terlalu membakar mulut. Tapi sekarang banyak kapur putih yang dijual di pasar, warnanya terlalu putih. Seperti ada campurannya.”
Saat ditanya mana yang lebih berat menjaga kesehatan atau menjaga tradisi, Yokbeth menjawab mantap: “menjaga tradisi.”
“Karena budaya kita makin lama makin hilang. Susah sekali menjaga supaya budaya tetap hidup.”
Namun, ia menegaskan bahwa pilihan untuk berhenti makan pinang adalah urusan pribadi. Ia tak takut jika suatu hari memilih berhenti.
“Kalau saya berhenti, itu keputusan sendiri. Sekarang pun banyak anak muda dan orang tua yang sudah berhenti.”
‘Saya harap orang lain juga bisa berhenti, sebelum terlambat’
Kembali ke Welmince yang telah dinyatakan terbebas dari kanker mulut, dia berharap lebih banyak masyarakat sadar akan bahaya di balik kebiasaan mengunyah pinang yang selama ini dianggap biasa.
“Saya sudah tidak makan pinang lagi. Takut luka itu muncul lagi. Saya harap orang lain juga bisa berhenti, sebelum terlambat,” ujarnya.
Ia juga berharap pemerintah dan tenaga kesehatan lebih aktif turun ke kampung-kampung untuk mengedukasi warga.
“Banyak yang belum tahu kalau makan pinang bisa bikin kanker. Kalau bisa, puskesmas dan rumah sakit datang kasih penyuluhan,” ujarnya.
Sementara Kepala Unit Kemoterapi RSUD Jayapura, dokter Jan Frits Siauta, mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai upaya menekan kasus kanker mulut.

Sumber gambar, Muhammad Ikbal Asra
Dokter Jan menyebut bahwa rumah sakit sudah melakukan edukasi, namun masih terbatas pada pasien yang datang berobat. Ia pun mengakui bahwa penyuluhan di masyarakat luas, khususnya di daerah terpencil, masih sangat minim.
“Pencegahan itu kuncinya. Tapi kita masih terlalu fokus pada pengobatan. Seharusnya yang dikedepankan adalah promosi kesehatan dan upaya preventif.”
“Sayangnya, itu butuh tenaga dan biaya yang besar, apalagi di wilayah geografis seperti Papua yang sulit dijangkau,” paparnya.
Dia berharap pemerintah mulai serius membangun strategi jangka panjang untuk menekan kanker, termasuk melalui promosi kesehatan di masyarakat akar rumput.
“Kita harus libatkan tenaga kesehatan di pelosok, karena pencegahan adalah kunci utama,” tegasnya.

Sumber gambar, Muhammad Ikbal Asra
Akan tetapi, salah satu generasi muda di Papua, Yokbeth Felle, memprediksi akan ada penolakan jika pemerintah atau rumah sakit datang ke kampung dan menyarankan warga untuk berhenti mengunyah pinang.
“Pasti kontradiktif, karena pinang sudah lama hidup bersama masyarakat. Lebih baik pemerintah cek kapurnya. Pastikan aman untuk dikonsumsi.”
Yokbeth juga mengingatkan bahwa bagi banyak keluarga, pinang adalah sumber penghidupan.
“Banyak mama-mama Papua hidup dari jual pinang. Jadi larangan total bukan solusi. Kita butuh pendekatan yang menghormati budaya.”
Reportase oleh wartawan di Jayapura, Muhammad Ikbal Asra.




